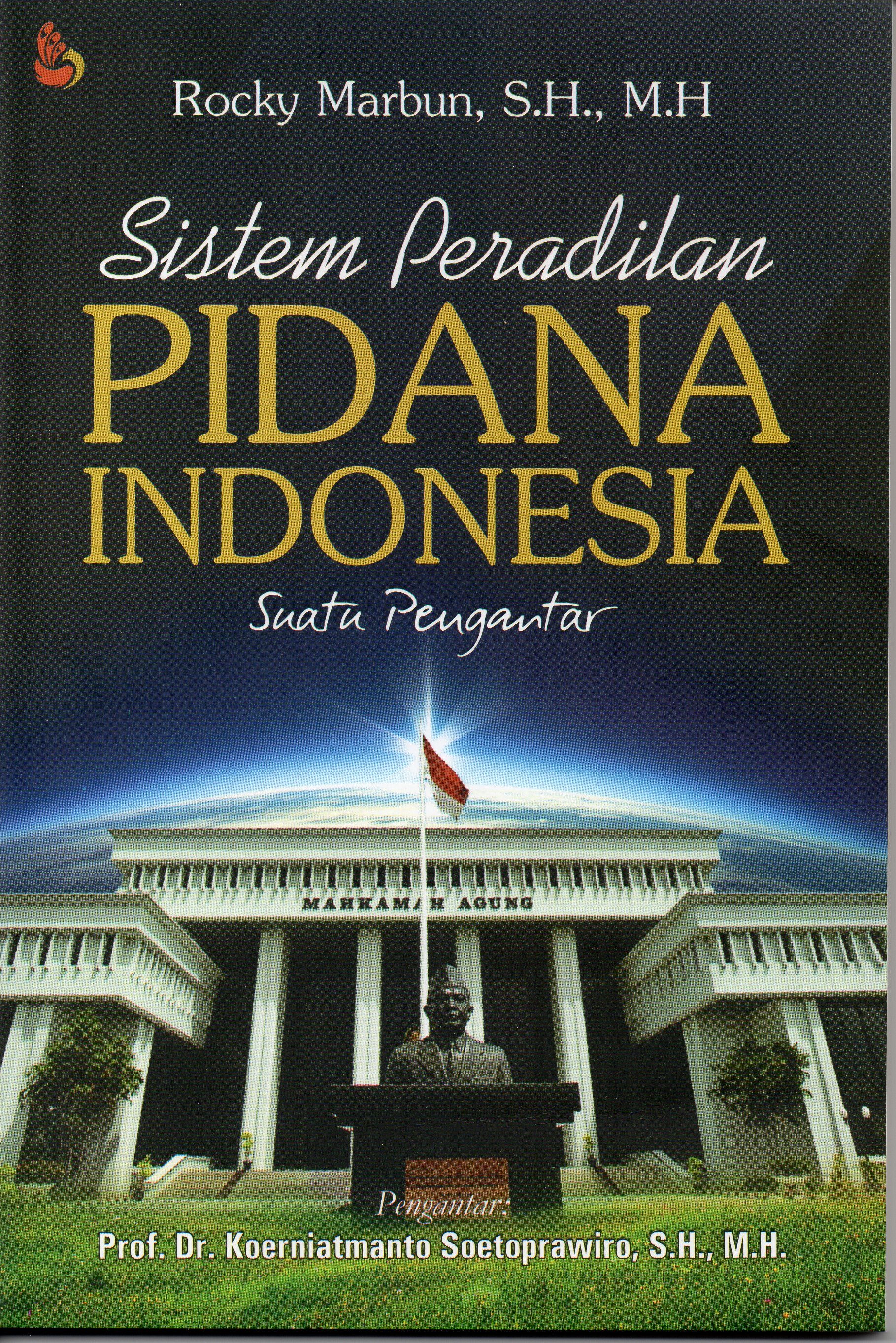Oleh:
Rocky Marbun[1]
A. Pendahuluan
“FIAT JUSTITIA ET PEREAT MUNDUS”
Hukum Harus Ditegakkan Meskipun Dunia Akan Hancur.
Suatu adagium yang mencoba menampilkan sebuah semangat dalam melakukan law enforcement yang sangat luar biasa. Bahkan dapat dikatakan sebuah adagium yang penuh dengan keniscayaan, kesia-siaan, dan kemustahilan serta tidak realistis. Namun adagium tersebut, menjadi cambuk bagi para pihak yang hidup dan penghidupannya bersinggungan dengan berbagai masalah hukum.
Layaknya mata uang yang memiliki dua sisi, disatu sisi semangat melakukan law reform (reformasi hukum) melalui proses law enforcement secara due process of law seakan-akan tidak pernah padam, baik Akademisi dan Praktisi Hukum selalu dengan lantang menyuarakan asas-asas dan norma-norma hukum yang selayaknya diterapkan dalam praktek. Namun di sisi lain, hilangnya semangat dan kepercayaan kepada hukum sebagai ujung tombak dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum oleh sebahagian besar masyarakat.
Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan.
Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.[2]
Kerumitan proses peradilan pidana tersebut diperparah dengan aksi lepas tangan dari Pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga seolah-olah proses peradilan pidana menjadi eksklusif bagi masyarakat. Kondisi tersebut tidak saja berlangsung pada saat proses peradilan pidana terjadi, namun pada fase pemidanaan atau putusan pengadilan hingga eksekusi putusan, keterlibatan masyarakat sangat diabaikan. Masyarakat seolah-olah menjadi pihak yang tidak berkepentingan atas proses peradilan pidana, dari hulu hingga hilir, sehingga tujuan idee des recht (Ajaran Cita Hukum)[3] yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan dan manfaat, sangat tidak dirasakan.
Menurut Mudzakkir, mengatakan bahwa KUHAP sendiri memang cenderung menjadikan sanksi penjara sebagai primadona hukuman atas terpidana. Sanksi hukuman lain hanya dianggap sebagai sanksi alternatif. Karena itu, tidak heran jika-hakim-hakim yang mengadili kasus-kasus pidana menjadikan penjara sebagai sanksi utamanya. Padahal sebenarnya keadilan yang diharapkan masyarakat, khususnya korban tindak pidana, lebih dari itu. Mudzakkir mencontohkan, kasus pembunuhan seorang kepala rumah tangga. Terhadap kasus tersebut, negara memang mewakili keluarga korban menghukum pelaku. Namun, kebutuhan istri korban setelah kasus selesai tidak lagi jadi perhatian negara. Terhadap nasib istri korban selanjutnya, negara sepertinya cuci tangan. Namun, pelaku yang terbukti bersalah justru dipenjara atas biaya negara.[4]
Keterwakilan masyarakat dari proses peradilan pidana, dari hulu hingga hilir, menjadi sebuah keharusan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Namun pada saat ini, hal tersebut menjadi suatu keniscayaan karena terbentur dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang menafiqkan / menghilangkan peran serta masyarakat. Walaupun di beberapa peraturan perundang-undangan pidana, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, termuat ketentuan mengenai pentingnya peran serta masyarakat. Namun hanya terbatas pada pemberian informasi kepada aparat hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.
Keterwakilan yang Penulis maksudkan adalah keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya proses peradilan pidana terkait keterkaitannya masyarakat baik sebagai pihak korban maupun pihak pelaku.
Minimnya akses masyarakat dalam proses peradilan pidana adalah menjadi suatu kewajaran, dikarenakan mindset (pola pikir) pembentukan peraturan perundang-undangan pidana adalah domain dari Pemerintah. Dimana sebagai lembaga negara yang memperoleh mandat untuk melaksanakan aspirasi rakyat melalui pembentukan kebijakan peraturan perundang-undangan pidana, ternyata tidaklah menjadikan masyarakat menjadi stakeholder dalam merumuskannya.
Kesemerawutan dalam merumuskan kebijakan peraturan pidana dewasa ini, tidak lagi hanya berawal dari ketidakmampuan dalam membaca faktor sosiologis dan historis dari perkembangan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Namun juga didasari atas ketidakmampuan dalam memahami asas-asas dan teori-teori hukum pidana yang berkembang. Kondisi tersebut di support dengan masuknya kepentingan-kepentingan segelintir dari sebahagian kelompok masyarakat yang mampu merubah tatanan idealis menjadi oportunis dan pragmatis.
Berjalannya Sistem Peradilan Pidana (SPP) sangat tergantung kepada berjalannya sistem penegakan hukum itu sendiri. Sehingga tak jarang para ahli hukum menyamakan makna antara SPP dengan sistem penegakan hukum (Barda Nawawi Arief, 2006: 6). Berbicara penegakan hukum, maka tak terlepas pula dengan tujuan hukum itu sendiri. Dimana tujuan hukum hendaknya mampu mensinergiskan antara pemenuhan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, bukan hanya kepada korban, namun juga kepada pelaku tindak pidana dan masyarakat sebagai komunitas tempat akhir kembalinya si pelaku.
Pewacanaan restorative justice dalam sistem hukum di Indonesia memberikan warna baru dalam proses penegakan hukum, khususnya pada sistem peradilan anak. Namun pada proses penegakan hukum secara umum, penal mediation yang merupakan pewujudan dari retorative justice, seringkali dipergunakan secara tebang pilih.
Peranan institusi penegak hukum dalam proses penegakan hukum seringkali terpaku kepada redaksional pasal-pasal yang dimaknai secara kaku. Kewenangan yang diberikan dalam ranah H.A.N., pada institusi polisi dan jaksa, dan dalam ranah Kekuasaan Kehakiman, pada institusi badan peradilan, tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal. Pola pikir yang terpolakan berdasarkan pandangan legal positisme, sehingga membentuk perilaku penegak hukum dalam memahami hukum dilakukan secara linear, deterministik dan mekanistik.
Penegakan hukum yang didasarkan kepada retributive theory, sudah tidak selayaknya dipergunakan, khususnya dalam upaya-upaya mengembalikan religius magis masyarakat. Penerapan penal mediation dalam proses penegakan hukum saat ini tidak dilandaskan kepada ketentuan-ketentuan yang terukur dan jelas. Akibatnya perkara yang diakhiri dengan adanya perdamaian antara para pihak, justru tidak menimbulkan keadilan dan kemanfaatan bagi mereka.
Sebagai pembanding, Penulis mencoba untuk menguraikan kepastian hukum yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak melalui ‘lembaga maaf ’ dalam Hukum Islam (islamic law), yang disandingkan dengan unsur keperdataan yaitu kafarat atau diyat (denda) kepada keluarga korban ataupun keluarga ahli warisnya, yang dipergunakan dalam ranah jarimah qishah.
Penulisan makalah bertujuan untuk mencoba kemungkinan-kemungkinan dikolaborasikannya kaidah dalam ushul fiqh ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Fakta hukum yang melandasi pemikiran dalam penulisan karya ilmiah ini adalah semakin overload-nya penghuni Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tujuan hukum hukum pidana yang selama ini diusung, telah terbukti tidak mampu, jangankan mengurangi, menekan tingkat kejahatan yang ada.
B. Tujuan Hukum Yang Legalistik Formal
M. Yahya Harahap (1993 : 41) pernah mengungkapkan bahwa KUHAP yang mengadopsi upaya penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), maka seharusnya implementasi dalam praktek oleh para penegak hukum terkait pasal-pasal yang termuat di dalam KUHAP pula mencerminkan penghormatan terhadap HAM tersebut.
Sehingga pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana bukan saja hanya terfokus kepada pengenaan derita, sebagai konsekuensi dari putusan pengadilan, namun juga pemenuhan hak-hak terpidana pasca putusan pengadilan yaitu eksekusi dan proses pengembalian kepada komunitasnya. Hal ini tergambar dengan sudah tidak dipergunakannya lagi sistem kepenjaraan, namun telah beralih kepada sistem pemasyarakatan. Dimana termuat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang memberikan stigma terpidana sebagai Warga Binaan. Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan, bahwa penerapan sistem pemasyarakat bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Terkait dengan hal pemidanaan tersebut, patut disadari bahwa proses peradilan pidana, bukan saja berhenti hingga diberikannya sanksi pidana kepada pelaku, namun juga seharusnya Negara bertanggung jawab untuk dapat membentuk perilaku terpidana agar dapat diterima kembali kepada komunitasnya/masyarakat. Sehingga, Negara pun bertanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, agar muncul pemahaman bahwa dengan dijatuhkan dan dijalankan masa pemidanaannya maka kondisi kebatinan menjadi pulih kembali atau kembali kepada keadaan semula.
Sehingga tujuan dari pemidanaan bukan hanya terfokus kepada pemidanaan kepada pelaku namun juga patut dipertimbangkan atas pemenuhan rasa keadilan dari korban dan masyarakat.
Tujuan hukum tersebut saat ini semakin sulit terealisir, sebagaimana diungkapkan oleh Soetandyo Wignjosebroto (2012 : 9), bahwa sistem hukum di Indonesia terstruktur dengan prosedur-prosedur yang resmi dan terjelma menjadi apa yang disebut bureaucratic atau bureaucratized law, yang ironinya justru berseiring dengan inefisiensi dan ketidakefektifan usaha mengawal tertib kehidupan nasional. Kian berkembang sebagai bureaucratized law kian teralienasi pula hukum undang-undang negara dari suasana sosial-kultural rakyatnya sendiri.
Kegalauan tersebut menjadi wajar dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto, bahwa semakin berkembangnya sifat administratif dalam hukum pidana, yang bertujuan mencari kebenaran materiil telah bergeser menjadi mencari kebenaran formil, dalam artian bahwa keadilan prosedural telah menggeser keadilan substantif, sebagai akibat dari adopsinya Asas Legalitas di dalam konstitusi. Sebagaimana termuat di dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan sebagai berikut:
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”
Dengan demikian, secara tidak langsung pada frase “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”, yang merupakan pemaknaan yang terkandung di dalam Asas Legalitas (Eddy O.S. Hiariej, 2009: 24), menyatakan bahwa Negara Indonesia menundukan diri kepada paham legisme atau positivisme hukum. Yang pada akhirnya, implementasi undang-undang oleh penegak hukum hanya sebatas sebagai corong undang-undang atau “terompet undang-undang” (la bouche de la loi) yang dibatasi kepada pemenuhan unsur-unsur pidana.
Berkaitan dengan tujuan hukum tersebut, maka Thomas Aquinas merumuskan bahwa tujuan hukum tidak lain menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat secara umum. Rakyat dalam suatu Negara haruslah menikmati kesejahteraan umum itu. Pemerintah yang tidak menjamin rakyatnya menikmati kesejahteraan umum adalah pemerintah yang mengkhianati mandat yang diembannya. Pemerintah haruslah melaksanakan suatu Negara demi kesejahteraan antara lain melalui hukumnya yang adil. Kesejahteraan umum selain merupakan tujuan hukum, juga merupakan suatu prasyarat adanya masyarakat atau Negara yang memperhatikan rakyatnya. Kesejahteraan umum itu meliputi antara lain, keadilan, perdamaian, ketentraman hidup, keamanan, dan jaminan bagi warganya (Otong Rosadi, 2010: 278).
Thomas Aquinas berpandangan bahwa hukum positif yang adil memiliki daya ikat melalui hati nurani. Hukum positif akan disebut adil jika memenuhi syarat: diperintahkan atau diundangkan demi kebaikan umum; diperintahkan oleh legislator yang tidak menyalahgunakan kewenangan legislatifnya; dan memberikan beban yang setimpal demi kepentingan kebaikan umum.
C. Masyarakat Indonesia Adalah Masyarakat Yang Religius
Di dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan sebagai berikut:
“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”
Frase tersebut mencirikan secara jelas, bahwa dalam perikehidupan bangsa Indonesia, tidak menampik adanya campur tangan ilahi dalam sejarah perjalanan bangsa.
L.W.C. van den Berg (1845-1927) merupakan sarjana Belanda pertama yang diangkat sebagai penasehat khusus Pemerintah Kolonial Belanda dalam bidang Bahasa-Bahasa Timur dan Hukum Islam (eastern language and Islamic law), ditugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para Pejabat Pemerintah Kolonial Belanda menyangkut ajaran Islam terkait dengan kehidupan sehari-hari umat Islam.
Van den Berg bertugas di Indonesia (1870-1887), dengan teorinya Receptio in Complexu: “Hukum penduduk setempat (dan juga orang-orang Timur lainnya) sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh agama yang dianut sejauh tidak ada bukti lain yang menolaknya. Sebab dengan menerima dan menganut suatu agama berarti sekaligus juga menerima aturan hukum dari agama yang dianutnya tersebut. Jika terdapat bukti yang sebaliknya atau “sebuah pengecualian” berupa atauran-aturan tertentu, maka kekecualian tersebut harus dipandang sebagai “deviasi” dari hukum agama yang telah diterima secara complexu.
Hukum Islam dipandang sebagai hukum yang hidup dan berlaku (the living law) bagi umat Islam. Teori ini didasarkan pada keyakinan Van den Berg bahwa “Islam telah diterima secara baik oleh sebagian besar, jika tidak semua, umat Islam setempat.” Teori Van den Berg ini kemudian diresmikan melalui Aturan Pemerintah Kolonial Belanda Nomor 152 tahun 1882. Yang sebelum juga diakomodir dalam beberapa kententuan yang terdapat pada Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch Indie (R.R.), Stbl. Nomor 129 tahun 1854 dan Nomor 2 tahun 1855, terutama pasal-pasal 75, 78, dan 109. Dan pada masa Daendels dan Raffles, hukum yang berlaku bagi umat Islam Indonesia adalah hukum Islam.
Pada perkembangan berikutnya dimunculkan Teori Receptie oleh Christian Snouck Hurgronje dan dikembangkan lebih lanjut oleh Cornelis Van Vollenhoven dan Ter Haar, yang menyatakan bahwa hukum Islam baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Terpahami di sini bahwa hukum Islam berada di bawah hukum adat. Oleh karena itu, jika didapati hukum Islam dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat pada hakikatnya ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat (Mohd. Idris Ramulyo : 1995). Yang kemudian dipatahkan oleh Teori Receptio a Contrario dari Hazairin dan Sajuti Thalib. Namun berdasarkan Pasal 131 IS, bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat.
Hal ini wajar karena penerapan Hukum Adat akan lebih menguntungkan bagi penjajah pada saat itu. Dan untuk menghindari sisi negatif, penjajah mengapungkan Hukum Adat yang memang menunjang terhadap misi mereka. Dengan demikian, benar kiranya kalau hukum adat dimaksudkan oleh bangsa penjajah untuk melumpuhkan gerak langkah pelembagaan hukum Islam yang bermuara kepada tercapainya misi penjajahan mereka.
Dikaitkan dengan Hukum Islam sebagai salah satu unsur pembentuk hukum nasional, ketika muncul perdebatan mengenai pengaturan tindak pidana kesusilaan, dimana menurut Oemar Seno Adji, delik kesusilaan di ancam pidana di Indonesia bukan karena di muka umum, tetapi menurut pandangan agama perbuatan melanggar kesusilaan itu dilarang (Andi Hamzah, 1987: 31).
Oleh karena itu, pemikiran dalam karya ilmiah ini dilandasi kepada kenyataan bahwa dari tahun 1981 hingga akhir Tahun 2012, semangat legal reform yang dibawa oleh KUHAP rupanya tidak menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Hal tersebut dikarenakan sistem peradilan pidana, secara global, masih mengacu kepada pemikiran-pemikiran bernuansa kolonialisme. Sehingga sistem peradilan pidana di Indonesia masih tidak terlepaskan dari pemahaman yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa.
Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusuma-Atmadja, dimana Beliau menegaskan bahwa hukum adalah salah satu dari kaidah sosial (di samping kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan lain-lain), yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (Shidarta, et.al., 2012: 19).
D. Infiltrasi, Bukan Islamisasi
Gagasan tentang hukum ilahi dalam Islam biasanya diekspresikan dengan kata fiqh (fikih) dan syari’at (syariat). Fikih, secara orisinal, bermakna pemahaman dalam pengertian yang luas. Seluruh upaya untuk mengelaborasi rincian hukum ke dalam norma-norma spesifik negara, menjustifikasinya dengan perujukan kepada wahyu, mendebatnya atau menulis kitab dan risalah tentang hukum merupakan contoh-contoh fikih. Jadi, kata fikih menunjuk kepada aktivitas manusia dan para sarjana, khususnya, untuk menderivasi hukum dari wahyu Tuhan (Taufik Adnan Amal & Samsu Rizal Panggabean, 2004: 1).
Hubungan antara agama dan negara sepanjang sejarah Islam merupakan masalah penting, tak terkecuali di Indonesia, sehingga menarik minat para ahli untuk melakukan kajian. Telah banyak kajian dilakukan dan pemikiran ditawarkan, dari berbagai sudut pandang. Namun demikian, diskusi, yang beberapa diantaranya merupakan polemik di kalangan cendikiawan muslim, hingga kini belum selesai (Jazuni, 2005: 1).
Penerapan Hukum Islam secara murni merupakan suatu kemustahilan, jika persyaratan utama dalam sistem hukum islam tidak terpenuhi. Bahwa prinsip-prinsip ketauhidan merupakan langkah awal yang perlu dikedepankan yang kemudian disandingkan dengan Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Sehingga, desakan-desakan yang muncul dari beberapa golongan dari ummat Islam, akan menjadi suatu keniscayaan, jika proses pemberlakuan syariat Islam dilakukan dalam proses pemaksaan kehendak.[5]
Umat Islam sendiripun, saat ini, akan lebih mudah mencerna tujuan hukum menurut teori-teori hukum yang sudah lebih dahulu dikenal dibandingkan mengenal tujuan hukum menurut syariat Islam. Sehingga sangat wajar, ketika bermuncullan pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu: “Kejamkah Hukum Islam?”
Bahwa sangat penting untuk memahami tujuan dari disyariatkannya hukum Islam atau lebih dikenal dengan istilah maqashid syari’ah. Imam Al-Ghazali dalam membahas Maqashid tidak memberikan batasan secara rinci mengenai pengertian Maqashid Syari’ah terkecuali hanya mengatakan bahwa; “wa maqshudu al syar’i min al khalqi khamsatun wa hiya: ’an yahfadha lahum dinahum wa nafsahum, wa ‘aqlahum wa naslahum wa mãlahum” (tujuan syariat Allah SWT bagi makhluk-Nya adalah untuk menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal, keturunan, dan harta mereka). Namun demikian, hukum pidana Islam (fiqh jinnayah) tidaklah seketat dan sekaku apa yang selalu digaungkan.
Sejarah perjalanan sistem pemidanaan di seluruh dunia mengalami pasang surut, fakta realita yang muncul ke permukaan adalah teori-teori pemidanaan yang ada justru menambah jumlah pelaku tindak pidana dan bukan menimbulkan efek jera, baik kepada pelaku yang telah dipidana maupun calon pelaku tindak pidana. Sehingga dimunculkanlah konsep pemidanaan terbaru yaitu restorative justice.
Menurut Tony F. Marshall (Joana Shapland, 2008: 1), restorative justice adalah : “Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.”
(Terjemahan bebas ==> Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang).
Menurut pandangan Michael Tonry, restorative justice mempunyai pengaruh besar karena kemapuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan.
Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restorative Justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan (Bagir Manan, 2008: 4). Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep “restorative justice”.
Munculnya konsep restorative justice, pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh fiqh jinnayah, sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah: 178
“Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula.”
Disyariatkannya diyat merupakan salah satu bentuk keringanan dari Allah SWT dari hukuman qishah atas suatu pembunuhan dengan sengaja, dan merupakan anugrah dan rahmat bagi umat manusia karena membebaskan dari pengaturan sebelumnya (Ibnu Katsir, 2000 : 132)
Untuk memasuki sistem hukum Islam secara langsung akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum yang wajib untuk dilalui. Sehingga Penulis berpendapat, bahwa pewacanaan restorative justice merupakan pintu gerbang guna lebih mengimplementasikan atau mengkonkritkan amanat yang terkandung di dalam pemberlakukan lembaga diyat ke dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
E. Kesimpulan
Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan dari 33 Kanwil Provinsi, 28 diantaranya mengalami over capacity tahanan atau narapidana. Tempat penahanan yang secara khusus dinyatakan sebagai rumah tahanan negara masih tetap jumlahnya yaitu sebanyak 264. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya sebanyak 291 rumah tahanan. Rumah tahanan tidak bertambah, justru narapidana yang bertambah. Sejak tahun 2007 ada 86.550 narapidana, pada tahun 2013 meningkat menjadi 108.143 narapidana.
Kewenangan-kewenangan dalam mengeluarkan diskresi, pada ranah pra-adjudikasi, dan kewenangan melakukan rechtsvinding dan rechtsschepping, pada ranah adjukasi, seringkali diterapkan hanya berdasarkan status dan golongan dari pihak pelaku tindak pidana. Sedangkan kepentingan hukum dan kondisi batin korban dan/atau keluarganya menjadi semakin terabaikan.
Semangat legal reform yang diusung semenjak Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 yang mengusung perubahan KUHP dan semangat legal reform pada hukum formil dengan munculnya KUHAP, hingga desakan diamandemennya KUHP dan KUHAP, masih sangat sedikit sekali penegak hukum yang mampu mengejawantahkan kewenangannya, karena terbelenggu dengan paham legisme.
Sehingga semangat legal reform dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang sistematis, maka pembaharuan tidak hanya sekedar merubah atau mengamandemen peraturan perundang-undangannya saja, namun harus mencakup 3 (tiga) pilar dari sistem hukum, sebagaimana diklasifikasikan oleh Friedmann, yaitu struktur, subtansi dan kultur.
Masuknya wacana restorative justice, saat ini sudah diadopsi secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dengan memunculkan lembaga divertion (diversi), dapatlah dimanfaatkan untuk memasukan unsur keharusan membayar denda (diyat) sebagai bentuk manifestasi dari kerugian korban dan/atau keluarga ahli warisnya.
Yang pada akhirnya, ujung dari penerapan lembaga diyat yang disandingkan dengan permaafan, melalui proses dan konsrp restorative justice, justru akan menekan jumlah pelaku tindak pidana.
Daftar Pustaka
Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2006
Amal, Taufik Adnan, & Samsu Rizal Panggabean, Politik Syariat Islam. Dari Indonesia hingga Nigeria, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004
Hamzah, Andi, Pornografi Dalam Hukum Pidana. Suatu Studi Perbandingan, Jakarta : Bina Mulia, 1987
Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Jilid I, Jakarta : Pustaka Kartini, 1993
Hiariej, Eddy O.S., Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga, 2009
Jazuni, Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
Katsir, Al Imam Ibnu, Tafsir Ibnu Katsir. Juz 2, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000
Manan, Bagir, Retorative Justice (Suatu Perkenalan),dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI 2008
Rosadi, Otong, Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, September 2010.
Shapland, Joana, Restorative Justice And Prisons, Presentation to the Commission on English Prisons Today, 7 November 2008
Shidarta, et.al., Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan. Eksistensi dan Implikasi, Jakarta: Epistema Institute, 2012
Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri ini?, dalam Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial, 2012
“LBH: Kerusuhan LAPAS Terjadi Karena Over Kapasitas” http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/20/lbh-kerusuhan-lapas-terjadi-karena-over-kapasitas, diakses 21 Agustus 2013.
[1] Makalah ini pernah dipresentasikan pada Konferensi Nasional III Assosiasi Filsafat Hukum Indonesia dengan tema “Melampaui Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat”, yang diselenggarakan oleh AFHI, Epistema Institue dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, pada tanggal 27-29 Agustus 2013. Makalah ini masih dalam format aslinya, belum mengalami perubahan.
[2] Laporan Akhir Komisi Hukum Nasioanl (KHM) mengenai “Hak Memperoleh Akses Peradilan Pidana”, http://www.komisihukum.go.id
[3] Ada ahli hukum yang menyebutnya sebagai Teori Gabungan. Teori ini dicetuskan oleh Gusav Radbruch, ahli hukum yang berasal dari Jerman.
[4] “Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restrorative Justice”, sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6140/sistem-peradilan-pidana-sebaiknya-terapkan-irestorative-justicei-, Kamis, 01 Agustus 2002, diakses pada tanggal 20 Agustus 2013.
[5] Cermati perdebatan atas diberlakukannya Peraturan Daerah Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, khususnya pada Pasal 4 ayat (1), yang menegaskan sebagai berikut: “Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, dirumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong atau tempat-tempat lain di daerah.”