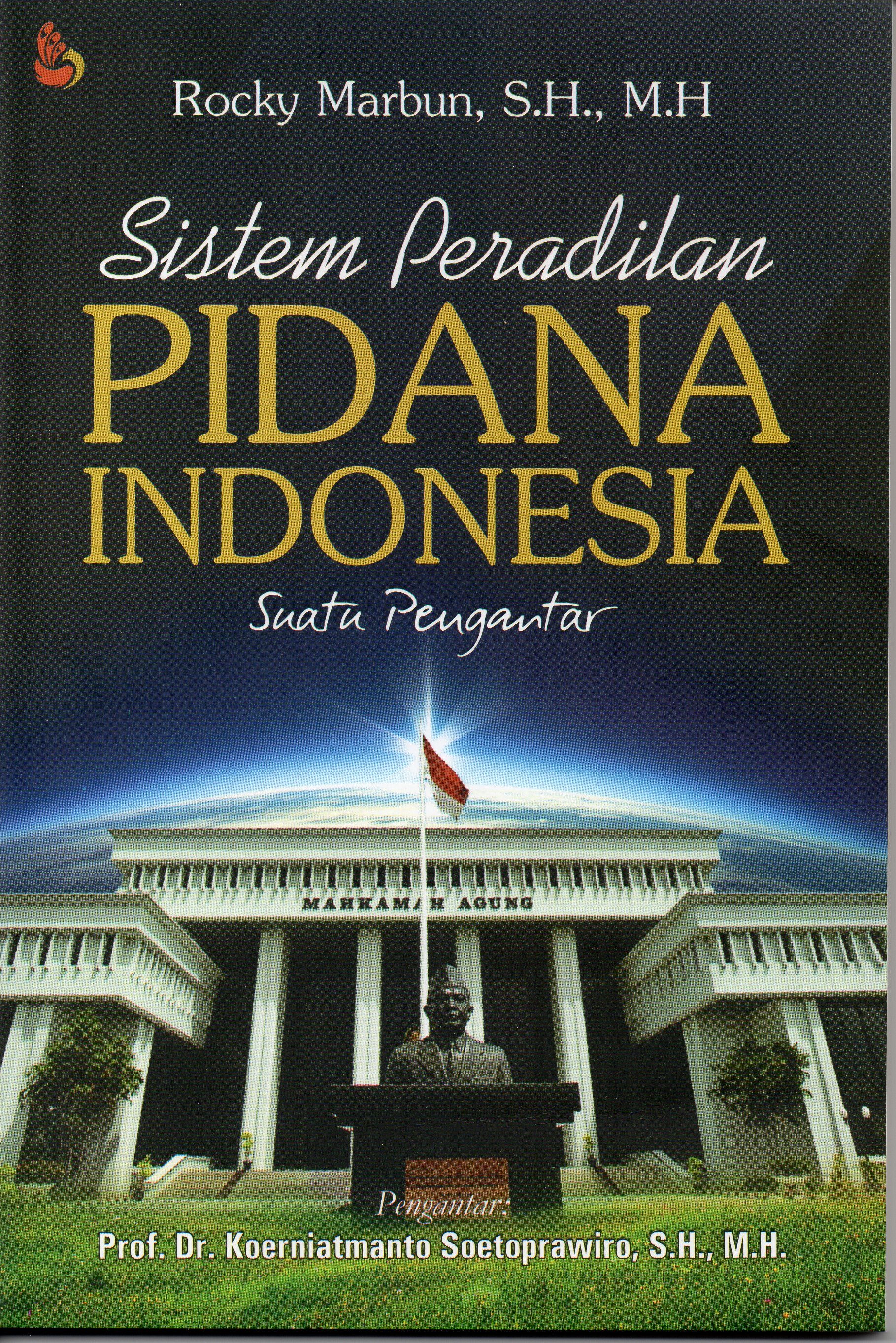Oleh:
Rocky Marbun, S.H., M.H.
Rasanya hampir tidak terbantahkan pandangan bahwa politik determinan terhadap hukum. Prof Moh Mahfud MD menjelaskan di dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, menguraikan panjang lebar secara ilmiah dan akademis berkaitan mengenai tarik menarik antara politik dan hukum dalam membentuk suatu kebijakan umum penguasa dalam membentuk Politik Pembangunan Hukum Nasional atau dalam dunia akademis seringkali disebut dengan istilah “Politik Hukum”. Namun untuk dapat memberikan suatu ketegasan bahwa pandangan tersebut benar ataukah tidak tidak sesederhana itu, karena memang masing-masing ahli hukum memandang berdasarkan perspektif yang berbeda-beda.
Satu hal yang pasti adalah kajian mengenai politik hukum disepakati sebagai suatu kajian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ilmu Hukum itu sendiri. Politik Hukum diyakini merupakan “kawah candradimuka” dari pembentukan suatu Sistem Hukum Nasional berdasarkan falsafah pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Maka penentuan Politik Hukum tersebut memiliki tujuan akhir kepada tujuan bernegara sebagaimana termuat di dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), yaitu kesejahteraan umum (bestuurzorg).
Berkaitan dengan hal tersebut, Padmo Wahyono pernah menjelaskan bahwa politik pembangunan hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kaitan dengan pelaksanaan dari keseluruhan kegiatan kenegaraan dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu (1). Penyelenggaraan kehidupan negara. Adapun yang dimaksud dengan bidang penyelenggaraan negara ialah bidang yang bersangkut paut dengan kelangsungan hidup organisasi negara, yang meliputi pembentukan mekanisme perundang-undangan sebagai kelanjutan dari hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, menyelidiki pasal-pasalnya, bagaimana penerapannya, suasana kebatinannya, perumusan teks perundang-undangan, suasana terciptanya teks perundang-undangan tersebut, keterangan-keterangan berkaitan proses pembentukannya, dimana kesemuanya berkaitan dengan pengaturan yang terdapat di dalam konstitusi mengenai organisasi kenegaraan. Dalam bidang ini perlu dicatat beberapa tahap pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara yang dipengaruhi oleh keadaan dan waktu; (2). Penyelenggaraan kehidupan sosial, adapun yang dimaksud dengan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah penyelenggaraan kehidupan negara lebih menentukan hal wahana yang memadai untuk mencapai tujuan bernegara, maka penyelenggaraan kehidupan sosial menentukan dan membentuk tingkat-tingkat perekonomian guna mencapai tujuan bernegara yang pada dasarnya bersifat dinamis. Di dalam bidang ini merupakan tahapan fungsional dari mekanisme garis-garis besar daripada haluan negara.
Pernyataan kehendak oleh Negara sebagai suatu kebijaksaan umum tersebut yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai salah satu konsekuensi logis dari dianutnya asas Negara Hukum. Dengan demikian, langkah konkrit dari perwujudan dari Politik Hukum tersebut adalah rangkaian kegiatan berupa perencanaan, perumusan dan pengundangan sejumlah nilai-nilai (values) ke dalam rangkaian norma di dalam beberapa perundang-undangan. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan tersebutlah yang kemudian dijadikan landasan dan batasan dari pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan dari Penyelenggara Negara. Landasan dan batasan tersebut kemudian dilimitasi oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) khususnya pada Pasal 7 ayat (1).
Dalam konteks implementasi suatu perundang-undangan, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu Undang-undang semenjak disahkan dan diundangkan telah membawa cacat lahir dan cacat bawaan, yaitu keterbatasan dalam menjangkau perubahan-perubahan sosial yang sangat dinamis di dalam masyarakat. Maka, konsep negara hukum memberikan perpanjangan tangan bagi setiap Penyelenggara Negara untuk menetapkan suatu peraturan kebijaksanaan dalam bentuk tindakan hukum faktual berdasarkan asas diskresi (discretionary theory). Sehingga, di dalam proses penyelenggaraan negara seringkali kita mendengar produk-produk hukum yang bersifat petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk tehnis (juknis).
RASIONALITAS SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015 TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN (hate speech)
Ketentuan-ketentuan tertulis yang memiliki bentuk berupa petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk tehnis (juknis) tersebut seringkali kita jumpai dalam praktek kenegaraan memiliki nomenklatur berupa SURAT EDARAN. Eksistensi Surat Edaran (SE) yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk tehnis (juknis) memiliki peranan yang sangat penting bagi proses praktek penyelenggaraan negara. Setiap Pejabat Publik/Penyelenggara Negara dalam suatu institusi yang menerbitkan Surat Edaran (SE) tersebut adalah mengikat secara internal. Maka, Surat Edaran (SE) bukan merupakan peraturan perundang-undangan karena bersifat peraturan kebijakan (beleidsregel).
Namun, baik dalam ranah teoritis maupun praktis, pemaknaan berkaitan dengan Surat Edaran (SE) tersebut juga tidak seragam. Prof. Jimly Asshiddiqie misalnya, mengklasifikasikan Surat Edaran (SE) ke dalam bentuk quasi legislation yang berisi norma-norma aturan yang bersifat administratif yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman kerja. Adapun menurut Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah ditegaskan bahwa Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Sedangkan jika kita kaji melalui Pasal 8 UU PPP maka terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain selain yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPP, bahkan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memuat 2 (dua) syarat, yaitu (1). Diperintahkan oleh Undang-undang; dan (2). Dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian, pengkajian terhadap suatu Surat Edaran (SE) mengacu pada kedua syarat tersebut. Namun, jika tidak terpenuhinya kedua syarat itu maka suatu Surat Edaran (SE) hanya merupakan aturan internal yang tidak dapat memuat norma hukum baru.
Persoalan mengenai Surat Edaran (SE) tersebut di dalam kehidupan hukum di Indonesia sangat jarang sekali mengalami permasalahan-permasalahan yang memunculkan perdebatan-perdebatan baik dalam ranah teoretis maupun praktis. Sebagai contoh Mahkamah Agung RI seringkali mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang sifatnya menganulir suatu pasal tertentu di dalam suatu Undang-Undang, namun tidak banyak yang melakukan protes ataupun tidak banyak terjadi perdebatan akademik, kecuali mengenai SEMA tentang Peninjauan Kembali.
Saat ini, fokus perhatian masyarakat dan pemerhati hukum terarah kepada Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) tertanggal 8 Oktober 2015. Semenjak Surat Edaran (SE) tersebut bergulir, pro kontra sudah mulai marak. Berbagai opini dan asumsi sudah digulirkan, dan memang tidak dapat dipungkiri kemuncullan Surat Edaran (SE) tersebut seringkali dikaitkan dengan kondisi perpolitikan nasional khususnya kepada kinerja kepemimpinan nasional, yang seringkali ditampilkan dalam bentuk digital atau dalam ranah dunia maya melalui instrument internet. Sehingga, sudah dapat diprediksi para netizen (pegiat dunia maya) langsung bereaksi sebagai bentuk protes terhadap kebebasan berekspresi melalui media sosial (medsos).
Prof Yusril Ihza Mahendra (New.liputan6.com-4/11) berpandangan bahwa Surat Edaran (SE) tersebut tidak atau bukan merupakan pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, dengan dalih pengaturan yang dimuat di dalam Surat Edaran (SE) tersebut telah ada di KUHP dan Undang-undang khusus lainnya. Namun berbeda lagi dengan pandangan dari Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun (News.viva-3/11) yang menyatakan Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian seharusnya tidak usah diumumkan. Sebab kalau polisi terlalu ‘over acting‘ terhadap surat edaran ini maka akibatnya justru bisa mengancam kebebasan sipil.
Kondisi yang serupa pula nampak pada ranah praktisi, dimana Ketua MPR Zulkifli Hasan (Rakyat Merdeka-4/11) menyatakan mendukung polisi mempidanakan penyebar kebencian di media sosial. Sedangkan Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Rahmat Bagja berpendapat, Surat Edaran (SE) Kapolri merupakan bentuk lain dari pasal penghinaan terhadap Presiden yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Terhadap kondisi kegaduhan seperti ini, Polri melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Agus Rianto (News.viva-3/11) mengatakan Surat Edaran Kapolri ini diperlukan untuk memberi batasan dalam mengunggah sesuatu yang dapat menimbulkan kebencian, penghinaan dan lain sebagainya.
Dalam hal tersebut, Polri mengkonstruksikan suatu argumentasi guna menemukan kebenaran ilmiah yang didasarkan kepada fungsi Polri (Pasal 2 UU 2/2002 jo Angka 2 huruf e SE Kapolri No. 6/2015) yaitu memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun ruang lingkup SE Kapolri No. 6/2015 tersebut antara lain: dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampain pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Sedangkan perilaku yang diatur di dalam SE Kapolri No. 6/2015 tersebut adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong. Oleh karena itu, payung hukum yang digunakan untuk mendukung SE Kapolri No. 6/2015 tersebut adalah KUHP, UU HAM, UU Polri, Konvensi Hak EKOSOB, Konvensi Hak SIPOL, UU ITE, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Penanganan Konflik Sosial, PERKAP tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan PERKAP tentang Tehnis Penanganan Konflik Sosial. Sedangkan pada ranah penegakan hukum, secara tegas SE Kapolri No. 6/2015 tersebut berdasarkan kepada Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 28 jis Pasal 45 ayat (2) UU ITE, dan Pasal 16 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Adapun jika pelarangan-pelarangan yang telah diatur tersebut memunculkan konflik sosial maka SE Kapolri No. 6/2015 berjalan dengan menggunakan UU Penanganan Konflik Sosial dan PERKAP tentang Tehnis Penanganan Konflik Sosial.
Demikianlah rasionalitas yang hendak dibangun oleh Polri dimana didasarkan kepada fungsi kepolisian tersebut memunculkan kewenangan Polri dalam melakukan penanganan yang lebih efektif dan efesien untuk mencegah 2 (dua) hal yaitu terjadinya suatu tindak pidana karena Ujaran Kebencian (hate speech) dan konflik sosial karena Ujaran Kebencian (hate speech).
DEKONSTRUKSI TERHADAP SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015 TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN (hate speech)
Jika kita hendak melakukan dekonstruksi terhadap Surat Edaran (SE) tersebut, hendaknya diawali dengan dengan mengajukan terlebih dahulu beberapa presuposisi (pra-anggapan atau asumsi) yang relevan, yaitu:
- Apakah Surat Edaran (SE) tersebut merupakan produk hukum?
Di dalam ranah hukum pidana, dikenal suatu istilah apa yang disebut dengan Asas Legalitas. Secara peristilahan asas tersebut dimanifestasikan dengan suatu adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali atau “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Namun, jika kemudian rasionalitas dari Surat Edaran (SE) tersebut disandarkan kepada aturan tertulis sebagaimana dimaksud dengan Asas Legalitas. Maka, terjadi ketidaksinkronan pemaknaan dan tujuan dari Surat Edaran (SE) tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Asas Legalitas tersebut harus ditarik kembali ke dalam pemaknaan awal.
Hal tersebut dikarenakan pemaknaan Asas Legalitas yang saat ini dipahami merupakan kristalisasi dari pandangan Anselm von Feuerbach yang berakar dari pandangan Montesquieu dan Immanuel Kant, yang kemudian dikembangkan oleh Julius Stahl dalam salah satu karakteristik asas negara hukum yaitu penyelenggaran negara berdasarkan hukum, yang pada saat itu diartikan sebagai perundang-undangan, atau wetmatigeheid van bestuur. Namun semenjak adanya putusan Hoge Raad Tahun 1919, makna hukum sudah tidak lagi hanya sebatas perundang-undangan semata tetapi pula termasuk asas kepatutan dan asas kelayakan yang hidup di dalam masyarakat.
Beranjak dari uraian tersebut, maka pemaknaan Asas Legalitas adalah merupakan suatu asas yang memiliki dua fungsi secara bersamaan sekaligus yaitu (1). Pembatasan terhadap kekuasaan dan kewenangan terhadap penyelenggaraan negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan; dan (2). Pedoman berperilaku bagi setiap warganegara. Maka Surat Edaran (SE), dalam presuposisi adalah merupakan hukum¸ merupakan suatu beleidregel (peraturan kebijakan) yang dikeluarkan berdasarkan diskresi menjadi terikat dengan stufenbau theory (Teori Norma Berjenjang) yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Oleh karena itu, Surat Edaran (SE) harus memiliki pijakan dasar dari ketentuan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang.
Mengacu kepada Pasal 2 UU 2/2002, dimana ditegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Guna melaksanakan fungsi kepolisian tersebut dibatasi kekuasaan dan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU 2/2002 jo Pasal 2 KUHAP jo Pasal 3 KUHAP. Ketentuan-ketentuan tersebut bila dikaitkan dengan kekuasaan dan kewenangannya dalam melakukan proses peradilan pidana. Sedangkan ketentuan-ketentuan bila menjadi pembatasan kekuasaan dan kewenangan serta dasar hukum bagi perilaku Polri sebagai Penyelenggara Negara hendaknya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomr 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.
Maka kemudian yang menjadi permasalahan utama adalah apakah Surat Edaran (SE) tersebut dilandaskan kepada perundang-undangan yang mana?
Sepanjang penelusuran bahan hukum primer, suatu Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kapolri, Penulis meraba dengan menarik legalitasnya melalui Pasal 15 ayat (1) huruf e jo Pasal 15 ayat (2) huruf k jo Pasal 16 ayat (1) huruf i UU 2/2002. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka diketahui bahwa pelaksanaan fungsi kepolisian berada di dalam dunia ranah yaitu tindakan yang merupakan bagian proses peradilan dan tindakan yang merupakan bagian dari perilaku administratif peradilan pidana. Dimana kedua perilaku tersebut seringkali berjalan secara beriringan sehingga sangat sulit untuk dibedakan. Walaupun tidak ditegaskan secara langsung oleh ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga pada prinsipnya ketentuan tersebut merupakan legitimasi terhadap tindakan faktual dari suatu fungsi kepolisian, dan bukan legitimasi terhadap tindakan yang bersifat keputusan tertulis.
Jika Surat Edaran (SE) tersebut merupakan juklak dan juknis mengenai penanganan terhadap tindak pidana yang telah diatur di dalam Undang-undang, maka dimana letak dari Surat Edaran (SE) tersebut terhadap Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Hal tersebut disebabkan Surat Edaran (SE) tersebut tidak menunjukan adanya kekhususan sehingga menjadi penting harus dikeluarkannya Surat Edaran (SE). Baik KUHP, UU HAM, UU Polri, Konvensi Hak EKOSOB, Konvensi Hak SIPOL, UU ITE, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan UU Penanganan Konflik Sosial tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan kewenangan untuk Surat Edaran (SE) itu.
- Apakah Kapolri berwenang mengeluarkan Surat Edaran (SE) tersebut?
Mengacu kepada uraian pada point (1) tersebut, seolah-olah Kapolri memang berwenang mengeluarkan Surat Edaran (SE) tersebut. Namun dari struktur produk hukum secara internal nampak jelas Surat Edaran (SE) tersebut seolah-olah berdiri sendiri. Berbeda dengan munculnya PERKAP yang memang mendapat kewenangan secara atribusi melalui Pasal 15 ayat (1) huruf e UU 2/2002. Maka, menjadi summir keberadaan Surat Edaran (SE) tersebut dikarenakan dilakukan pengumuman ke muka publik.
Namun, jika dikaji kembali darimana ditarik kewenangan tersebut? Maka terdapat satu Undang-undang yang “seolah-olah” memberikan kewenangan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dimana di dalam Surat Edaran (SE) tersebut terdapat beberapa redaksional yang dianggap melegitimasi munculnya Surat Edaran (SE) No. 6/2015, yaitu:
Angka 2 huruf e Surat Edaran (SE) No. 6/2015, yang menegaskan sebagai berikut:
“bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, “sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian” tersebut;
Angka 2 huruf f Surat Edaran (SE) No. 6/2015, dimana pada bagian akhir menegaskan sebagai berikut:
“dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.”
Angka 2 huruf i Surat Edaran (SE) No. 6/2015, yang menegaskan sebagai berikut:
“bahwa dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian “apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien”, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, “akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas”, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.”
Angka 3 huruf b point 2 Surat Edaran (SE) No. 6/2015, yang menegaskan sebagai berikut:
“Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian, dalam penanganannya tetap berpedoman pada: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tehnis Penanganan Konflik Sosial.”
Dengan demikian, salah satu rasionalitas dari Surat Edaran (SE) No. 6/2015 adalah akibat sosial dari suatu ujaran kebencian yang menciptakan konflik sosial. Maka untuk menentukan adakah kewenangan Polri dalam membuat Surat Edaran (SE) No. 6/2015 tersebut.
Di dalam UU 7/2012 memberikan pengertian “Konflik Sosial” sebagai berikut:
“Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.”
Sedangkan pengertian dari “Pencegahan Konflik” adalah sebagai berikut:
“Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.”
Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) UU 7/2012 sebagai berikut:
“Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.”
Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sedangkan upaya yang hendaknya dibangun sebagai bentuk pencegahan konflik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU 7/2012, yaitu sebagai berikut:
- Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- Meredam potensi Konflik; dan
- Membangun sistem peringatan dini.
Dengan demikian, pihak-pihak yang melaksanakan upaya pencegahan tersebut adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan pelimpahan kewenangan secara langsung kepada Polri untuk melakukan tindakan pencegahan terjadinya konflik. Namun perlu dipahami kewenangan tersebut tidak bersifat independen, karena UU 7/2012 mensyaratkan tiga komponen yaitu Presiden, Kepala Daerah dan masyarakat yang terdiri dari Pranata Adat dan Pranata Sosial.
Sedangkan keterlibatan Polri secara langsung adalah berkaitan sebagai komponen dalam pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial yang bersifat ad hoc. Namun pembentukan Satgas tersebut hanya bisa dilakukan dengan syarat, yaitu:
- Tidak ada Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik;
- Tidak berfungsinya Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik;
- Tidak berjalannya mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial;
- Tidak tercapainya kesepakatan melalui mekanisme musyawarah Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; dan
- Telah ditetapkannya Status Keadaan Konflik.
Kekuasaan dan kewenanan Polri di dalam Satgas tersebut dibatasi oleh kekuasaan dan kewenangan Kepala Daerah selama masa konflik. Sehingga bukan merupakan pilar utama dalam penyelesaian konflik sosial. Dengan demikian, jika Surat Edaran (SE) No. 6/2015 tersebut ditujukan kepada upaya tindakan pencegahan dini adalah hal yang absurd dan tidak memiliki landasan kewenangan berdasarkan UU 7/2012.
Dengan demikian, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa kewenangan tertinggi yaitu kewenangan atribusi berada di tangan Presiden dalam melakukan serangkan tindakan pencegahan sebagai sarana peringatan dini. Sedangkan Kapolri secara lex specialist terhadap UU 7/2012, hendaknya harus dilakukan pendelegasian terlebih dahulu kepada Polri. Oleh karena ketentuan Pasal 2 UU 2/2002 merupakan ketentuan yang bersifat lex generalist. Dengan demikian, Kapolri tidak berwenang menggunakan UU 7/2012 sebagai dasar hukum dalam mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 6/2015 tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Surat Edaran (SE) No. 6/2015 bukanlah merupakan produk hukum dan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat siapa pun, kecuali hanya bagi Polri itu sendiri.
- Apakah suatu Surat Edaran (SE) dapat mengatur norma hukum baru?
Berdasarkan pengertian dari Surat Edaran (SE) baik berdasarkan teoretis maupun praktis, sebagaimana telah dijelaskan diawal, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa suatu Surat Edaran (SE) merupakan naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
Berdasarkan rasionalitas yang dibangun oleh Polri terhadap dikeluarkannya Surat Edaran (SE) No. 6/2015 adalah tindakan administratif yang sia-sia. Oleh karena, kekuasaan dan kewenangan Polri dalam melakukan penanganan terhadap hate speech telah diatur di dalam berbagai perundang-undangan pidana. Sedangkan mekanisme penyidikannya, selain secara lex specialist telah ada didalam perundang-undangan yang bersifat lex specialist tersebut, pula telah dimuat di dalam KUHAP dan PERKAP 14/2012. Sehingga tidak ada hal yang baru berkaitan dengan juknis maupun juklak bagi Penyidik.
Namun jika kita cermati dengan baik Surat Edaran (SE) No. 6/2015 tersebut maka terdapat muatan norma baru yang justru merupakan suatu pelanggaran terhadap asas legalitas itu sendiri. Misalnya, terdapat kalimat sebagai berikut:
Pada Angka 3 huruf a point 2, yang menegaskan sebagai berikut:
“melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personil Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gelaja-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.”
Pada Angka 3 huruf a point 5(d), yang menegaskan sebagai berikut:
“apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:………..”
Pada Angka 3 huruf b point 1, yang menegaskan sebagai berikut:
“penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan:………..”
Dengan demikian, jelas sekali bahwa Polri memunculkan jenis tindak pidana baru di dalam Surat Edaran (SE) No. 6/2015 yang merupakan pelanggaran terhadap Asas Legalitas. Pandangan ini menjadi relevan dengan dimunculkannya instrumen “dalam orasi kegiatan kampanye”, “ceramah keagamaan” dan “penyampaian pendapat di muka umum” dengan metode generalisasi.
Untuk membela pandangan tersebut, Kami mengajukan argumen sebagai berikut:
Di dalam Al Qur’an Surat Al-Baqaraah ayat 120 yang artinya sebagai berikut:
“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sebelum kamu mengikuti agama mereka.”
Jika sekiranya pendengar ayat ini ketika diucapkan di dalam masjid atau mushalla dalam media ceramah, adalah beragama selain Islam, dapatkan kemudian si non Islam tersebut melaporkannya sebagai hate speech? Apakah dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Ujaran Kebencian? Namun demikian, jika kondisi sosial yang memang dalam kondisi berpotensi muncul konflik sosial, kemudian ayat tersebut terus dikumandangkan, sangat mungkin saja terjadi Pihak Polri berpendapat hal tersebut adalah termasuk kepada hate speech. Namun, bukan karena isinya yang dapat dikategorikan sebagai hate speech, tetapi kondisi kondusiflah yang harus dibangun sehingga meredam isi dari ceramah menjadi penting. Sedangkan isi dari ayat itu sendiri bukanlah kategori hate speech.
Atau, Kami mencoba meletakan kondisi antara “ceramah keagamaan” dengan “dalam Orasi kegiatan kampanye”.
Di dalam kondisi perpolitikan di Indonesia yang bersifat pluralistik, maka persinggungan kepentingan seringkali terjadi. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, nampak sekali terjadi gesekan antara kepentingan sekelompok agama dengan kepentingan berbasis politik. Misalnya dengan majunya Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Calon Presiden.
Di dalam Al Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat 34 ditegaskan sebagai berikut:
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.”
Kemudian diperkuat dalam Hadist Nabi:
“Diriwayatkan dari Abu Bakrah, katanya: Tatkala sampai berita kepada Rasulullah bahwa orang-orang Persia mengangkat raja puteri Kaisar, Beliau bersabda: Tidak akan pernah beruntung keadaan suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada seorang perempuan.” (HR. Bukhari, Turmudzi dan An-Nasa’i)
Di dalam masa kampanye untuk kepentingan Ibu Megawati Soekarnoputri, ketika ayat dan hadist tersebut dikumandangkan di dalam berbagai ceramah-ceramah keagamaan, maka pertanyaanya adalah apakah ayat dan hadist tersebut merupakan perilaku hate speech? Yang kemudian didukung dengan argumentasi bahwa kelompok-kelompok yang tidak menyukai pemimpin wanita memanfaatkan ayat dan hadist tersebut untuk kepentingan politiknya. Hal tersebut tentunya kembali kepada orientasi seseorang atau sekelompok orang yang memisahkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara atau memisahkan antara agama dan politik.
Apakah yang demikian yang dimaksud dalam Surat Edaran (SE) No. 6/2015? Dengan demikian, apa yang diutarakan pada prinsipnya merupakan korelasi dengan kondisi pada saat diucapkan. Bahwa asasinya ucapan-ucapan tersebut adalah benar adanya, namun dalam kondisi yang tidak tepat. Sehingga, Surat Edaran (SE) No. 6/2015 tersebut justru memunculkan norma yang bersifat sangat abstrak dan lentur dan dapat saja ditarik berdasarkan kepentingan seseorang atau sekelompok.
Berdasarkan uraian dari dekontruksi Surat Edaran (SE) No. 6/2015 tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa Surat Edaran (SE) No. 6/2015 bukan merupakan produk hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Bahwa Surat Edaran (SE) No. 6/2015 tersebut tidak mengikat siapapun selain Polri sendiri. Oleh karena bukan merupakan produk hukum, Surat Edaran (SE) No. 6/2015 tersebut tidak memiliki nilai-nilai akademis dan bahkan menurut Kami, pula tidak memiliki nilai-nilai praktis karena sudah diatur oleh perundang-undangan pidana dan PERKAP 14/2012.
DAMPAK SOSIAL SEBAGAI AKIBAT DARI SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015 TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN (hate speech)
Ilmu Hukum adalah ilmu normatif maka hendaknya tetap berada di dalam keciri-khas-annya, namun demikian, tidak menutup diri dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial yang memang memiliki kedekatan hubungan dengan ilmu hukum. Namun tidak berarti harus ahli hukum menguasai ilmu sosial pula. Dan di dalam perkembangan Hukum Pidana melalui pergeseran filsafat hukum pidana terjadi pergeseran karena dipengaruhi oleh bidang Kriminologi, maka perlu juga memperhatikan perkembangan dari filsafat pemidanaan yang telah berkembang dewasa ini.
Berdasarkan objek kajian Ilmu Hukum adalah tata hukum positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan wilayah tertentu, maka seyogyanyalah kajian terhadap Ilmu Hukum Pidana pula didasarkan kepada pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri dalam melihat perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Penelaahan tersebut menjadi penting dalam memahami suatu perbuatan yang kemudian dianggap sebagai suatu perbuatan pidana yang berbasis asas legalitas sebagai parameter terciptanya suatu perbuatan pidana atau sebagai parameter terjadinya suatu perbuatan pidana dalam konteks sistem kemasyarakatan di Indonesia. Pandangan tersebut menjadi memiliki kesesuaian jika kita kembalikan kepada pandangan bahwa perbuatan pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan anti sosial. Maka hukum pidana bergerak sebagai hukum sanksi atas perbuatan anti sosial tersebut. Oleh karena itu, di dalam melakukan kegiatan rechtsbeoefening (pengembanan hukum praktis atau praktek hukum), maka di dalam penyusunannya guna dapat memerankan Ilmu Hukum dilakukan refleksi kefilsafatan terhadap Ilmu Hukum itu sendiri. Sehingga pemangku kepentingan akan mendapatkan gambaran yang utuh dari norma-norma yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan bukan lagi gambaran yang tereduksi terhadap norma-norma yang dilekatkan norma sanksi pidana.
Menurut Bernard Arief Sidharta bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari diabaikan atau kurang diperhatikannya studi Teori Argumentasi Yuridik (legal reasoning), dan terkait padanya Teori Penemuan Hukum, dalam pendidikan hukum di Indonesia memperkuat kecenderungan berpikir positivistik(-legalistik) dalam praktek hukum. Menyelesaikan masalah hukum secara yuridik dalam intinya berarti menerapkan aturan hokum positif terhadap masalah (kasus) tersebut. Menerapkan aturan hukum positif hanya dapat dilakukan dengan jalan secara kontekstual menginterpretasi aturan hukum tersebut untuk menemukan kaidah hukum yang tercantum di dalamnya dalam kerangka tujuan kemasyarakatan dari pembentukan aturan hukum itu (teleologikal) yang dikaitkan pada asas(-asas) hukum yang melandasinya dengan melibatkan juga berbagai metode interpretasi lainnya (gramatikal, historikal, sistematikal, sosiologikal).
Sehingga kegiatan Ilmu Hukum tersebut diatas dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan pokok Ilmu Hukum yang didasarkan kepada objek kajiannya yaitu fakta kemasyatakatan dan kaidah hukum.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pembahasan kaidah hukum telah Kami sampaikan diatas, oleh karena itu pada bagian ini akan dikonsentrasikan kepada pembahasan kepada faktor “fakta kemasyarakatan”.
Hukum dalam tataran praktis bergerak di dalam masyarakat, dimana masyarakat merupakan objek sekaligus sebagai subjek, karena asasinya adalah merupakan manusia, di dalam hukum. Sehingga, bukan hanya produk perundang-undangan saja yang berimplikasi kepada masyarakat, namun tindakan faktual penyelenggara negara justru memberikan implikasi yang bersifat langsung.
Polri merupakan komponen dari Sistem Peradilan Pidana, sebagai suatu bagian dari sebuah sistem maka kajian terhadap Polri, dalam perspektif Lawrence M Friedmann, terdiri dari legal structure, legal substance dan legal culture. Maka, di dalam konteks rechtsbeoefening, hukum tidak saja dipandang sebagai hal-hal yang semata-mata bersifat normatif, namun juga sisi praktek.
Perkembangan ilmu hukum, baik langsung maupun tidak langsung, turut terpengaruh dengan derasnya arus globalisasi. Hubungan internasional yang diejawantahkan melalui berbagai konvensi Internasional dan perjanjian internasional, baik yang bilateral maupun multilateral, turut pula mewarnai dan/atau menggeser sistem hukum Indonesia. Yang pada akhirnya menuntut pula perubahan pada pola pikir dan budaya hukum yang ada saat ini. Oleh karena itu, setiap Anggota Polri wajib memahami essensi dirinya sebagai Pejabat Publik/Administrasi Negara, yang memiliki kewenangan guna mengeluarkan kebijakan dan/atau kebijaksanaan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang humanis sesuai peraturan perundang-undangan. Kebuntuan dalam hal praktek, tidak serta merta dicarikan solusi melalui legal culture (budaya hukum) yang berkembang di institusi Polri. Karena budaya hukum itu sendiri bukanlah suatu kebenaran koherensi. Namun, perubahan dalam konteks budaya hukum merupakan bidang yang sangat sulit hingga saat ini. Sehingga adalah hal yang sia-sia manakala pembaruan Hukum Pidana hanya sebatas legal structure dan legal substance tanpa adanya pembaruan pada legal culture.
Cara pandangan Polri terhadap seseorang sebagai “terlapor” tidak bisa dilepaskan dari pengalaman sejarah yang telah mengakar dan mendarah daging melalui sistem pemeriksaan secara inquisatoir di dalam menerapkan KUHAP yang menganut sistem pemeriksaan accusatoir, tidak lah ada pembaruan secara utuh.
Di dalam Angka 2 huruf e Surat Edaran (SE) No. 6/2015, yang menegaskan sebagai berikut:
“bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, “sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian” tersebut;
Angka 2 huruf f Surat Edaran (SE) No. 6/2015, dimana pada bagian akhir menegaskan sebagai berikut:
“dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.”
Angka 2 huruf i Surat Edaran (SE) No. 6/2015, yang menegaskan sebagai berikut:
“bahwa dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian “apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien”, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, “akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas”, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.”
Terhadap frase-frase tersebut, di dalam konteks rechtsbeoefening (pengembanan ilmu hukum atau praktek hukum) bukan hanya dapat dipermasalahkan dengan bagaimana cara penggunaan metode interpretasi, namun bagaimana legal culture dalam menerapkan hasil interpretasi tersebut.
Kuatnya pengaruh mahzab positivisme di dalam Sistem Peradilan Pidana menjadikan Polri, yang telah ditetapkan sebagai “penegak hukum”, bertindak sebagai corong undang-undang (la bounche de la loi). Tak jarang, ketika seseorang yang diposisikan sebagai “terlapor” melakukan pembelaan diri tak jarang dibenturkan dengan kalimat yang terlontar “Kami hanya melaksanakan Undang-Undang”, atau “Keberatan Bapak/Ibu silahkan ajukan di dalam persidangan”. Sehingga kewenangan untuk melakukan penahanan menjadi sangat subjektif berdasarkan kekuasaan. Dengan demikian, legitimasi terhadap Polri sebagai “penegak hukum” ternyata tidak dapat memaknai kata “hukum” yang melekat di atas pundaknya. Terhadap hal tersebut, maka hendaknya dikaji pandangan dari Oliver Wendell Holmes, mantan Hakim Agung di Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang menjelaskan “To be master of any branch of knowledge, you must master those which lie next to it…..And thus to know anything you must knows all.”
Oleh karena itu, seseorang ahli hukum yang hanya berkutat pada ranah teoretis tidak akan mampu membayangkan rasa gundah gulana dan ketakutannya manakala seseorang yang diletakan sebagai “terlapor” mendapatkan Surat Panggilan dari Polri. Hal tersebut dikarenakan penggunaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang dimaknai sebagai kekuasaan. Sedangkan makna kewenangan pada hakikinya adalah pembatasan terhadap kekuasaan itu sendiri.
SIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:
- Surat Edaran (SE) No. 6/2015 bukanlah merupakan produk hukum, termasuk bukanlah produk perundang-undangan;
- Surat Edaran (SE) No. 6/2015 telah melanggar Asas Legalitas dengan menunculkan tindak baru yaitu Tindak Pidana Ujaran Kebencian;
- Surat Edaran (SE) No. 6/2015 justru memunculkan penafsiran yang sangat luas terhadap ujaran kebencian terkait dengan sarananya;
- Surat Edaran (SE) No. 6/2015 memunculkan kekuasaan dan kewenangan yang berlebih untuk melakukan tindakan sebagai pencegahan dini;
- Surat Edaran (SE) No. 6/2015 akan memunculkan kerugian psikologis dari seseorang yang diklasifikasikan sebagai pelaku ujaran kebencian;
*) Bahan Diskusi Kelompok Kelas Kimia 73 Fakultas Hukum Universitas Bung Karno